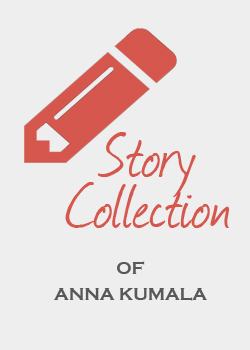“Giliran Anda, Angkasa!”
Dosenku menyebut namaku. Aku bangkit dari kursi dan
melangkahkan kakiku ke depan kelas sambil membawa memory chip yang memuat materi presentasiku. Aku sampai di depan layar
sentuh lebar dan membuka media presentasi yang telah kusiapkan dua minggu
terakhir.
Materi yang akan kubawakan tidak berbeda jauh dengan
teman-temanku yang lain. Tugas pertama mata kuliah wajib ini meminta kami untuk
menjelaskan tentang kemajuan teknologi secara umum dan menjabarkan dampak
kemajuan teknologi berdasarkan apa yang kami lihat. Semua yang kami
presentasikan harus berasal dari pemikiran kami sendiri, bukan dari buku
apalagi internet.
Aku menghubungkan layar sentuh dihadapanku dengan proyektor
yang memantulkan cahaya ke layar berukuran 6x8 meter di tengah ruangan. Saat
layar besar itu menampilkan bagian pembuka materi, aku memulai presentasi.
“Selamat pagi, teman-teman! Pagi ini, Saya, Angkasa, akan
membawakan materi tentang kemajuan teknologi dalam sudut pandang saya.”
Aku menekan tombol remote
control dan tampilan pada layar berganti. Layar yang sebelumnya menampilkan
halaman pembuka, kini menampilkan sebuah halaman dengan judul “Gambaran
Mengenai Kemajuan Teknologi”. Aku menghela napas panjang.
Agak sulit menyampaikan ini karena apa yang akan kusampaikan
kemungkinan besar bertentangan dengan sebagian besar isi kelas termasuk
dosenku. Aku memandang sekeliling ruangan, menatap setiap pasang mata yang
menantikan apa yang ingin kusampaiakan, lalu aku menunduk dan menghela napas
lagi.
“Angkasa, Saya tidak meminta Anda ke depan hanya untuk diam
dan menatap layar,” tegur Dosen. Ternyata tanpa sadar aku telah terdiam cukup
lama.
“Ah, maaf, Pak!
Saya segera melanjutkan,” sahutku.
“Menurut saya…” sepotong kata keluar lalu aku diam lagi. Aku
terdiam lagi sampai-sampai wajah dosenku terlihat sangat kesal. Tepat ketika
Beliau ingin mengatakan sesuatu, aku mengeluarkan kata lagi.
“Kemajuan teknologi …” aku kembali ragu untuk mengatakan apa
yang sudah kusimpulkan. Tapi, aku harus meneruskan presentasi ini jika aku ingin
lulus dari mata kuliah ini.
Wajah dosenku mulai tidak sabar. Beliau melangkah mendekat
ke arahku.
“Kemajuan teknologi…” dan aku hanya mengulangi kesalahanku.
Kali ini, dosenku benar-benar menghampiriku dengan wajah gusar.
-o0o-
“Jadi Saya akan kembali ke kota kelahiran Saya, Pak?”
“Ya, Saya baru mendapatkan email konfirmasi beasiswa studimu
di Universitas Ayashi.”
“Saya akan menjadi mahasiswa Universitas Ayashi, Pak? Universitas
yang luar biasa itu?”
Guruku tersenyum lalu mengangguk. “Iya, Angkasa. Kamu akan
ke Ayashi dan menjadi mahasiswa di universitas besar itu.”
“Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Saya berhutang pada
Bapak.” Aku mencium tangan guruku lalu melompat-lompat di sepanjang koridor.
Aku luar biasa bahagia. Setelah bertahun-tahun tidak kembali ke kota itu, aku
akhirnya punya kesempatan.
Ayashi adalah kota kelahiranku. Dulu namanya bukan Ayashi,
tapi Gerang. Kala itu Gerang bukan sebuah kota, melainkan kabupaten. Aku lahir
di pinggiran Kabupaten Gerang delapan belas tahun yang lalu dan hidup disana
bersama Ayah sampai beliau meninggal dunia. Ibuku meninggal dunia setelah
melahirkanku, jadi aku hanya dibesarkan oleh Ayah.
Ayah sangat menyayangiku. Beliau berjuang sangat keras untuk
bisa menyekolahkanku. Padahal, beliau hanya seorang penyembelih ayam di pasar,
pekerjaan yang bahkan tak disadari keberadaannya oleh kebanyakan orang. Ayah
selalu berkata bahwa apapun yang terjadi aku tidak boleh putus sekolah, aku
harus menjadi orang yang berpendidikan, aku harus bermimpi tinggi setinggi
namaku, Angkasa.
Aku dan Ayah tinggal di sebuah rumah kayu kecil yang memang
hanya cukup untuk kami berdua. Kami tinggal di dekat hutan, sedikit jauh dari
pusat pemukiman. Di depan rumah kayu kami mengalir sungai yang jernih. Aku
sekolah di SD dekat pasar. Jadi, setiap hari sekolah, aku biasanya ikut Ayah ke
pasar dan membantu menata ayam-ayam yang sudah disembelih. Kami biasa berangkat
dari rumah pukul dua dini hari agar pukul tiga kami sudah bisa tiba di Pasar
dan pukul empat ayam sudah bisa dijual oleh para pedagang.
Di sore hari sepulang sekolah, aku biasa bermain di dekat
pemukiman dengan teman-teman satu sekolahku. Dari mulai gobak sodor, petak umpet,
sampai lempar bata, rasanya permainan
kami tidak pernah habis dan kami tidak pernah merasa bosan.
Kehidupan seperti itu kujalani sejak aku mulai sekolah SD
sampai aku kelas empat SD. Di tahun itu, Kabupaten Gerang dibagi menjadi
Kabupaten Gerang dan Kota Gerang. Daerah pusat menjadi kota, sedangkan daerah
pinggiran seperti daerah tempat tinggalku ini menjadi kabupaten. Di tahun itu
juga sebuah pabrik didirikan dekat pemukiman kami. Aku tidak tahu pabrik apa
itu, yang aku tahu pabrik itu mengancam kehidupan di pemukiman kami.
Warga-warga berjatuhan meninggal dunia karena keracunan limbah pabrik, Ayah
termasuk salah satu yang meninggal. Aku sedih bukan main dan merasa sangat
marah, tapi tidak mengerti harus marah kepada siapa. Aku hanya bocah SD berumur
sepuluh tahun yang polos saat itu.
Pamanku lalu datang mengambilku dan merawatku sampai saat
ini. Beliau memperlakukanku dengan baik. Beliau bahkan bersedia menyekolahkanku
sampai tamat SD. Sisanya, aku berjuang dengan tangan dan kakiku sendiri. Aku
menjadi kuli angkut di pasar pada hari libur, menjadi loper koran setiap pagi sebelum
berangkat ke sekolah, berjualan es keliling di dekat jalan raya sepulang
sekolah, apapun yang bisa kulakukan agar bisa menjalankan pesan Ayah untuk
tidak putus sekolah.
Kota Gerang mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hanya dua
tahun setelah aku meninggalkan kota itu, ia berganti nama menjadi Ayashi. Ayashi
menjadi kota pertama yang diberi gelar kota teknologi di negeri ini. Ayashi
juga merupakan kota pertama yang memiliki universitas berbasis teknologi.
Sejujurnya aku tidak begitu mengerti apa yang mereka maksud kota teknologi dan
universitas berbasis teknologi. Satu-satunya yang aku tahu dari berita-berita
di surat kabar adalah bahwa Kota Ayashi dan Universitas Ayashi benar-benar
menakjubkan.
Aku tidak sabar untuk kembali ke kota itu. Mungkin aku bisa
bertemu dengan teman masa kecilku yang masih tinggal disana. Mungkin juga aku
bisa bertemu dengan anak pedagang ayam yang dulu sering membantuku menata ayam
yang sudah disembelih, atau mungkin aku bisa melihat lagi hutan lebat dan
sungai dekat rumah kayuku dulu. Entah apa yang akan kutemui disana, yang jelas
aku sudah tidak sabar untuk melihat kembali kota kelahiranku.
-o0o-
“Kenapa Anda tidak melanjutkan presentasi Anda, Angkasa?
Bagaimana saya bisa menilai Anda jika Anda hanya mengulang kata-kata yang
sama?” ujar dosenku sedikit gusar, terdengar dari suaranya yang agak meninggi.
“Maafkan Saya, Pak. Saya akan melanjutkan presentasinya,”
sahutku dengan nada sopan.
Sebelum melanjutkan, aku kembali menoleh kea rah dosenku dan
bertanya,”Pak, benarkah Saya boleh mempresentasikan apa yang saya lihat dan
saya pikirkan?”
“Bukan hanya boleh, Angkasa. Anda harus,” kata dosenku
tegas.
“Baiklah,” kataku akhirnya.
Aku menarik napas panjang dan melanjutkan presentasi,
“Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dua minggu terakhir, menurut saya
kemajuan teknologi adalah…”
-o0o-
“Selamat datang di kelas Pengembangan Teknologi! Saya Indra
dan Saya akan menjadi dosen Anda satu semester ke depan,” sapa dosen pertama
yang kelasnya kumasuki semester ini.
Aku sudah tiba di Ayashi sejak sebulan lalu, melewati
serangkaian orientasi perkuliahan, perjalanan keliling kota, dan pengenalan
tentang tujuan Universitas Ayashi secara umum. Kesan yang aku dapat selama
sebulan terakhir adalah luar biasa dan benar-benar sesuai ekspektasi. Kota ini
benar-benar rapih. Kota ini memiliki sistem industri yang baik, sistem
pengolahan sampah yang nyaris sempurna, teknologi terbaru, gadget tercanggih yang mendukung pembelajaran, akses internet
tercepat di negeri ini gratis tanpa batas untuk seluruh penduduk kota, angkutan
umum yang cepat dan murah dijalankan oleh sistem kontrol pusat.
Universitas Ayashi pun tak kalah hebat. Universitas ini
memiliki laboratorium super lengkap dengan keseluruhan sistemnya digital. Tidak ada lagi kertas, yang ada
hanya layar sentuh dimana-mana. Untuk mengajar, mencatat, mengerjakan tugas,
ujian, segalanya dilakukan dengan layar sentuh. Kota Ayashi adalah kota
terpintar yang pernah aku kunjungi dan Universitas Ayashi adalah aset berharga
di dalamnya.
“Saya akan memulai mata kuliah ini dengan tugas observasi
individu. Dalam tugas pertama ini, Anda diminta untuk melakukan observasi di
dalam Kota Ayashi mengenai kemajuan teknologi. Saya ingin masing-masing dari
Anda mempresentasikan tentang kemajuan teknologi secara umum dan dampak
kemajuan teknologi yang Anda amati sendiri. Rincian tugas dapat Anda lihat di
akun Anda masing-masing.”
Kami menyimak baik-baik apa yang ditugaskan dosen. Aku
membuka akunku dan membaca rincian tugas. Disana tertulis bahwa aku harus
membatasi daerah yang kuamati. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan bahwa daerah
yang akan aku amati adalah daerah pemukimanku. Daerah kecil di pinggiran Kota
Ayashi yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Gerang.
Kesanalah aku akan melangkah.
-o0o-
“Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dua minggu
terakhir, menurut saya kemajuan teknologi yang terjadi di Kota Ayashi mengarah
pada teori konspirasi yang bertujuan untuk menghancurkan kota ini sebagai awal
kehancuran negeri ini.”
Seisi kelas melotot ke arahku. Wajah dosenku mengernyit.
Beliau memotong presentasiku.
“Apa maksudnya ini, Angkasa?”
“Mohon maaf sebelumnya, Pak! Bisakah Saya melanjutkan
presentasi Saya terlebih dahulu?” kataku sesopan mungkin.
Dosenku tidak berkata apa-apa dan memersilahkan aku untuk
melanjutkan dengan isyarat.
-o0o-
Menangis.
Itulah hal pertama yang ingin kulakukan saat pertama kali
menginjakkan kaki di desa tempatku lahir ini. Tidak ada lagi hutan lebat atau
sungai jernih. Hutan telah terbabat menyisakan sangat sedikit pohon untuk
menyerap air dan sungai berubah menjadi keruh berlimbah pabrik. Kata orang di
desa, sistem pengolahan limbah ‘orang kota’ itu hanya bisa mengolah sebagian,
sedang sisanya dialirkan ke sungai ini. Warga desa sakit-sakitan, bahkan sudah
cukup banyak yang meninggal dunia akibat keracunan air berlimbah.
Pasar tempat aku dan Ayah dahulu bekerja, sekarang diubah
menjadi pasar modern dimana harga sewa kiosnya jauh lebih mahal. Jasa
penyembelih ayam dan kuli angkut tidak lagi digunakan, semua menggunakan mesin.
Warga desa banyak yang menjadi pengangguran, angka kriminalitas meningkat,
angka kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh kelaparan juga meningkat.
Anak-anak berhenti bermain permainan tradisional. Mereka
berhenti berinteraksi dan asik bermain dengan gadget mereka masing-masing. Tidak ada yang lebih penting daripada gadget mereka. Bahkan tidak juga
pendidikan dan orangtua mereka sekalipun. Tak jarang yang kemudian menjadi
‘berani’ kepada orangtua dan menjadi anak durhaka.
Akses informasi menjadi begitu mudah. Budaya malas
berkembang pesat. Bahkan para ‘kaum terpelajar’ berhenti mengamati lingkungan
sekitar karena malas dan menganggap semua sudah bisa diketahui dari dunia maya,
tidak perlu terjun langsung. Para siswa hanya terkonsentrasi bagaimana lulus
ujian dan memperoleh tiket melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Para
mahasiswa hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang akan memengaruhi penyematan
gelar sarjana di nama mereka. Mereka terlalu terobsesi dengan prestasi dan
kebanggaan, sampai-sampai lupa apa esensi belajar itu sendiri. Mereka lupa
bahwa pendidikan adalah untuk membekali diri agar dapat bermanfaat bagi
masyarakat sehingga yang terjadi adalah mereka lalai pada kehancuran masyarakat
yang terjadi persis di depan batang hidung mereka.
Dua minggu itu benar-benar memberikanku banyak pandangan
baru mengenai kemajuan teknologi. Aku menyadari bahwa kemajuan teknologi yang
tidak didukung dengan pembinaan karakter yang baik dapat menimbulkan masalah
yang menghancurkan tatanan masyarakat, moral, dan bahkan membunuh orang-orang
yang tidak ada kaitannya. Seperti sebuah teori konspirasi yang dirancang oleh
orang-orang yang bertujuan untuk menghancurkan negeri ini dari dalam.
-o0o-
“Kemajuan teknologi di kota ini menyebabkan pencemaran
lingkungan yang berujung pada menurunnya kesehatan masyarakat, meledaknya angka
pengangguran, meningkatnya angka kematian, rusaknya tatanan sosial, hancurnya
moral dan kemanusiaan, serta hilangnya kepekaan masyarakat berpendidikan. Semua
dampak negatif ini menyerang harta terpenting yang dimiliki negeri ini, yaitu sumber
daya manusia.”
Aku menghela napas sejenak sebelum melanjutkan. Kali ini
seisi kelas tampak tertarik menyimak presentasiku.
“Sumber daya manusia yang sudah tua dan berpendidikan
diserang dengan proyek-proyek berkeuntungan tak wajar yang berkedok untuk
memajukan negeri ini.
“Sumber daya manusia yang tua dan pekerja keras tapi tidak berpendidikan
dipaksa menjadi pengangguran karena mesin-mesin mengambil pekerjaannya.
Beberapa dipenjarakan karena menjadi pelaku kriminal, beberapa lagi keracunan
limbah yang tak bisa diolah alat-alat, dan sisanya mati kelaparan.
“Sumber daya manusia yang muda dan berpendidikan diserang
kreativitasnya dengan kemudahan akses informasi sehingga membuat mereka malas
berpikir dan menciptakan sesuatu yang baru. Mereka juga diserang moralnya
dengan berbagai jenis gadget yang
dilengkapi permainan dan aplikasi digital sehingga tidak akan ada sumber daya
manusia yang berkualitas di masa depan karena moral pendidiknya telah dirusak
terlebih dahulu.
“Sebuah negara yang sumber daya manusianya telah dirusak,
seperti apapun kekayaan sumber daya alamnya, tidak akan lagi mencapai
kemakmuran. Maka Saya rasa, tidaklah berlebihan jika saya mengatakan bahwa
kemajuan teknologi yang terjadi di kota ini adalah sebuah teori konspirasi
untuk menghancurkan negeri ini dimulai dari kota ini. Sebab tidak ada
pendidikan karakter manusia yang berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi
ini.
“Kita boleh saja berbangga karena karena teknologi yang
dimiliki kota ini jauh lebih hebat daripada kota lainnya di negeri ini, bahkan
jauh lebih hebat dari kota-kota di negara tetangga. Kota ini sangat pintar.
Hanya dengan mesin, kota ini dapat berjalan dengan begitu apik. Tapi, bagaimana
dengan kualitas manusianya? Apakah manusia di kota ini sama pintarnya dengan
kota ini sendiri? Apakah kita sama pintarnya dengan kota yang kita tinggali
ini?
“Kita patut mempertimbangkan tentang adanya teori konspirasi
yang bertujuan untuk menghancurkan kota ini sebagai awal kehancuran negeri ini.
Kalaupun ternyata teori ini tidak pernah ada, toh tidak ada salahnya memperbaiki kembali kualitas sumber daya
manusia yang telah bertahun-tahun rusak akibat kemajuan teknologi yang tidak
terkontrol.”
Seluruh isi kelas berdiri dan bertepuk tangan secara meriah.
Dosenku secara khusus datang ke depan kelas dan menyalamiku erat, lalu
memberikan tiga kali tepukan di bahuku.
“Angkasa, kau sungguh-sungguh mengamati!” ujarnya sambil
tersenyum.
Meskipun aku sendiri tidak tahu benar atau tidaknya teori konspirasi
itu, aku berharap semoga belum terlambat untuk kami mengembalikan hal-hal
positif yang hilang dari kota ini. Semoga masih sempat sebelum kota ini
benar-benar menjadi titik mula kehancuran negeri yang kucintai ini.
Bandung
14 April 2015